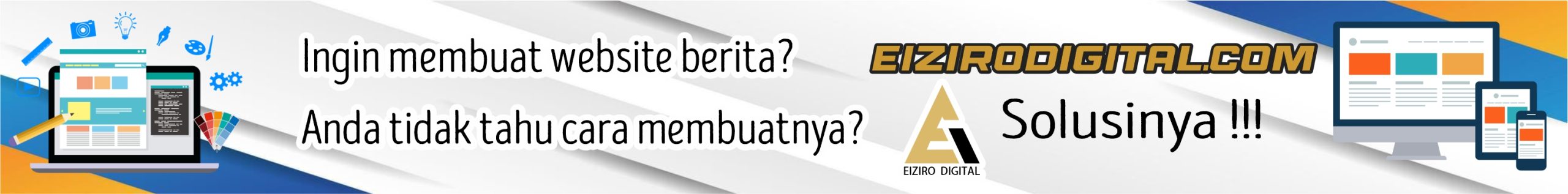Oleh: Ummu Fahhala
(Praktisi Pendidikan dan Pegiat Literasi)
Majalengka // zonakabar.com – Saya masih ingat pagi itu. Langit tampak muram, seolah memendam cerita panjang yang tak mampu ia sampaikan dengan kata-kata. Di sebuah warung bambu di lereng Banjarnegara, saya bertemu seorang lelaki tua bernama Pak Rofi’i. Tangannya gemetar saat ia menggenggam cangkir teh panas yang mulai kehilangan uapnya.
“Mas… tanah itu seperti manusia,” katanya pelan. “Kalau ia terus dipaksa bekerja tanpa istirahat, ia akan jatuh. Dan kita ikut jatuh bersamanya.”
Perkataannya sederhana, tetapi menghantam dada saya seperti pukulan. Karena pagi itu, berita dari berbagai daerah menyampaikan kabar duka yang sama: negeri ini kembali dilanda bencana.
Longsor di Cilacap masih menyisakan korban yang belum ditemukan meski operasi sudah berlangsung sepuluh hari. Di Banjarnegara, 27 warga diduga masih tertimbun material longsor. Banjir rob menghantam Kepulauan Seribu. Air bah mengepung berbagai wilayah dari Sulawesi Tengah, Aceh, hingga Sumatera Barat. Cuaca buruk, medan ekstrem, dan keterbatasan tim membuat BNPB dan BPBD bekerja ekstra keras. Namun alam seolah menggulung setiap upaya.
Kisah yang Mengalir: Antara Harapan dan Kegelisahan
Saya menatap Pak Rofi’i dan bertanya, “Menurut Bapak, mengapa kita terus diuji bencana seperti ini?”
Ia menghela napas panjang.
“Kita ini hidup di tanah yang subur, Mas. Tapi kesuburan itu punya aturan. Kalau aturan itu kita langgar, alam akan bicara. Dan ketika alam bicara… suaranya keras.”
Saya terdiam. Kata-katanya mengingatkan saya pada firman Allah Swt.: “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia.” (QS. Ar-Rum: 41)
Ayat itu seakan memantul dari lereng gunung di hadapan kami. Longsor yang menganga di kejauhan seolah menjadi tafsir nyata dari ayat tersebut.
Saat Kita Menyadari Akar Kerusakan
“Mas, lihat ke sana,” ujar Pak Rofi’i sambil menunjuk bekas tebing yang runtuh. “Dulu itu hutan. Sekarang jadi kebun. Lalu jadi perumahan. Tanah itu kehilangan pegangan.”
Saya memandang lereng itu lama. Hutan yang menghilang, bukit yang digerus, sungai yang menyempit, semuanya menjadi mozaik luka yang terus menganga. Kerusakan ini bukan sekadar teknis. Ia lahir dari arah pembangunan yang belum berpihak pada keseimbangan. Kita mengubah hulu tanpa memikirkan hilir. Kita membuka lahan tanpa memikirkan mitigasi. Kita membangun kota tanpa memikirkan resapan air. Dan ketika hujan turun, bumi tidak lagi sanggup menahan beban.
“Alam ini bukan sekadar ruang tinggal,” kata Pak Rofi’i. “Ia amanah.”
Kata-katanya kembali mengingatkan saya pada satu hadis Nabi Saw.: “Kaum Muslimin berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api.” (HR. Abu Dawud)
Hadis ini mengajarkan bahwa alam bukan komoditas. Alam adalah milik bersama yang harus dijaga, bukan dikuasai oleh segelintir pihak atas nama keuntungan.
Dialog di Antara Rintik Hujan
Hujan mulai turun. Kami berdua berlindung di bawah atap warung bambu.
“Sebenarnya bisa dicegah, Mas,” kata Pak Rofi’i. “Asal kita membangun dengan ilmu, dengan nilai, bukan hanya angka.”
“Ilmu dan nilai?” saya mengulang.
“Ya,” jawabnya. “Kita harus kembali pada aturan Tuhan. Hidup ini ada titahnya. Alam ada titahnya. Negara pun ada titahnya.”
Saya paham arahnya. Ia berbicara tentang prinsip besar yang lahir dari Islam, tentang bagaimana syariat memandang manusia, alam, dan negara sebagai satu kesatuan amanah.
Islam memandang bencana dari dua sisi: ruhiyah dan siyasiyah. Ruhiyah mengajarkan kita untuk mengambil pelajaran dan kembali pada Allah. Siyasiyah menuntut negara menjaga ruang hidup rakyat, melakukan mitigasi komprehensif, dan hadir penuh saat musibah datang.
Sejarah mencatat, ketika musim paceklik melanda Madinah, Umar bin Khattab turun langsung membangun dapur umum dan mengatur bantuan hingga rakyat aman. Itulah contoh kepemimpinan yang menjaga jiwa manusia.
Ketika Alam Mengajak Kita Pulang
Hujan reda. Pak Rofi’i berdiri dan menatap langit yang mulai menguning.
“Mas…” katanya pelan. “Alam ini seperti ibu. Ia mengasuh kita. Tapi kalau kita terus melukainya, ia menangis. Dan ketika ia menangis, air matanya jadi bencana.”
Saya terdiam lama. Karena saya tahu, kata-katanya bukan metafora kosong. Ia adalah kebenaran yang dipahatkan oleh pengalaman panjang hidup di lereng gunung.
Bencana tidak akan berhenti hanya dengan tanggap darurat. Bencana butuh perubahan paradigma. Bencana butuh arah baru yang menempatkan manusia, alam, dan Tuhan dalam satu garis lurus.
Allah Swt. berfirman: “Jika penduduk negeri beriman dan bertakwa, Kami akan melimpahkan berkah dari langit dan bumi kepada mereka.” (QS. Al-A’raf: 96)
Ayat ini adalah janji sekaligus peta jalan. Jika kita menjaga bumi, bumi menjaga kita.
Jika kita taat pada aturan-Nya, alam pun tunduk pada harmoni-Nya.
Mungkin inilah saatnya kita berhenti sejenak, mendengar suara alam yang lelah, dan kembali pada jalan yang menghidupkan, jalan yang pernah ditempuh oleh Nabi dan para khalifah, jalan yang menuntun manusia dan alam melangkah bersama dalam kedamaian.
Karena ketika alam memanggil kita pulang, ia sebenarnya mengajak kita kembali pada diri kita sendiri, nilai kita, fitrah kita, Tuhan kita, jalan yang benar yakni jalan Islam.