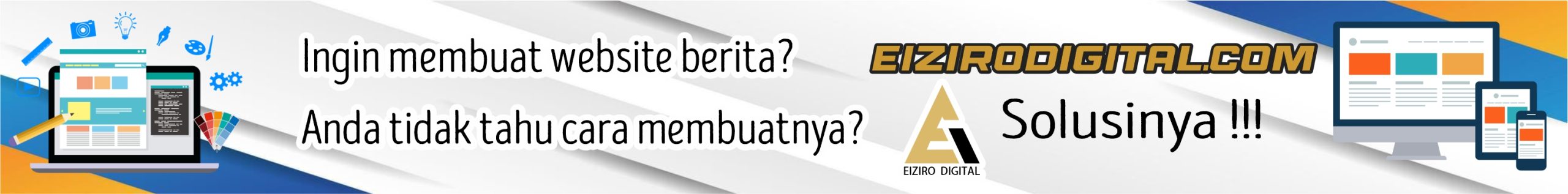Oleh: Ummu Fahhala, S.Pd.
(Praktisi Pendidikan dan Pegiat Literasi)
Majalengka // zonakabar.com – Malam itu turun perlahan, seolah tak ingin menyentuh tanah yang sudah terlalu lelah. Bau lumpur masih mengendap di udara, bercampur bau spanduk bantuan darurat. Di sebuah halaman sekolah yang kini tinggal kerangka, seorang anak duduk di atas papan reot sambil memegang pensil tumpul. Matanya menatap kosong pada ruang kelas yang roboh.
“Ayah,” ia bertanya pelan, “kapan sekolahku kembali?”
Pertanyaan itu jatuh seperti hujan pertama di atas luka: lirih, namun menghujam. Ayahnya terdiam. Ia ingin menjawab dengan optimisme, tetapi waktu tidak memberinya kepastian. Yang ia punya hanyalah rumor kalender, “Februari, mungkin,” ujarnya..
Senja itu terasa panjang. Atap-atap belum kembali, buku-buku hanyut, dan mata anak-anak menunggu lebih dari sekadar kabar. Mereka menunggu kehadiran.
Bencana alam tidak hanya meruntuhkan rumah dan infrastruktur, tetapi juga mengguncang fondasi masa depan sebuah bangsa, yaitu pendidikan. Banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November 2025 telah meninggalkan jejak kehancuran yang dalam.
Ribuan satuan pendidikan terdampak, ribuan ruang kelas rusak, dan ratusan ribu peserta didik terputus dari layanan belajar. Sekolah yang semestinya menjadi ruang aman dan pemulihan, justru berubah menjadi tempat pengungsian, kehilangan fungsinya sebagai pusat pembelajaran.
Data yang disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah menunjukkan skala krisis yang tidak kecil. Namun, besarnya dampak tersebut berbanding terbalik dengan kecepatan respons negara. Pemerintah memang menyatakan komitmen untuk memulai rehabilitasi dan pembangunan sekolah pada Februari 2026, tetapi jeda waktu yang panjang ini menyisakan pertanyaan mendasar: ke mana anak-anak harus belajar selama masa penantian itu?
Di sinilah persoalan utama muncul. Pendidikan dalam situasi darurat seolah diperlakukan sebagai urusan sekunder, menunggu stabilitas administratif dan anggaran, alih-alih diposisikan sebagai kebutuhan mendesak yang tak boleh ditunda. Narasi optimisme yang berulang, bahwa situasi akan terkendali dalam beberapa bulan, tidak otomatis menjawab realitas di lapangan. Tanpa ruang belajar, tanpa guru yang terorganisasi, dan tanpa dukungan psikososial, pendidikan sejatinya sedang mengalami stagnasi serius.
Lebih ironis lagi, inisiatif konkret justru banyak datang dari luar negara. Lembaga kemanusiaan, organisasi nonpemerintah, komunitas pendidikan, hingga relawan independen bergerak cepat membangun kelas darurat dan pendampingan belajar. Sementara itu, kebijakan pusat belum tampak secara tegas menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama dalam agenda pemulihan bencana. Situasi ini memunculkan kesan bahwa negara mengambil jarak, seolah hak belajar anak dapat menunggu hingga status darurat dicabut.
Padahal, hak atas pendidikan tidak mengenal jeda. Ia tetap melekat, bahkan dalam kondisi paling genting sekalipun. Ketika negara lambat bertindak, yang terancam bukan hanya keberlangsungan proses belajar, melainkan juga keberlanjutan generasi.
Perspektif Islam: Kepemimpinan yang Bertanggung Jawab
Dalam pandangan Islam, kepemimpinan bukan sekadar otoritas administratif, melainkan amanah untuk melayani dan melindungi rakyat. Al-Qur’an menegaskan kewajiban pemimpin untuk menunaikan amanah dan menegakkan keadilan (QS. An-Nisa’: 58). Rasulullah saw. juga mengingatkan bahwa setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya.
Sejarah Islam memberikan teladan konkret. Pada masa Umar bin al-Khattab, negara bergerak cepat memastikan kebutuhan dasar rakyat tetap terpenuhi di tengah krisis, termasuk pendidikan dan layanan sosial. Pemulihan pascabencana dipahami sebagai tanggung jawab moral dan politik negara, bukan beban yang dialihkan kepada masyarakat semata.
Berangkat dari prinsip ini, negara semestinya segera mengaktifkan strategi pendidikan darurat yang terintegrasi. Sekolah darurat harus dibangun tanpa menunggu rehabilitasi permanen rampung. Anggaran pendidikan perlu disesuaikan secara fleksibel melalui mekanisme darurat, bukan ditunda hingga tahun anggaran berikutnya. Guru dan tenaga pendidik harus dimobilisasi, layanan psikososial diperkuat, dan sistem pemantauan yang transparan diterapkan agar pemulihan berjalan efektif.
Penutup
Pemulihan pendidikan pascabencana bukan semata soal membangun kembali gedung sekolah. Ia adalah upaya menjaga martabat kemanusiaan dan masa depan bangsa. Ketika pendidikan satu generasi terabaikan, dampaknya akan menjalar jauh melampaui wilayah bencana.
Pemimpin sejati tidak berhenti pada pernyataan normatif dan optimisme simbolik. Mereka hadir melalui tindakan cepat, keberpihakan nyata, dan kebijakan yang memastikan tak satu pun anak kehilangan hak belajarnya karena kelambanan negara. Pendidikan bukan kemewahan dalam kondisi normal, dan terlebih lagi bukan kemewahan di tengah bencana, tetapi ia adalah hak yang harus dijaga kapan pun dan dalam keadaan apa pun.