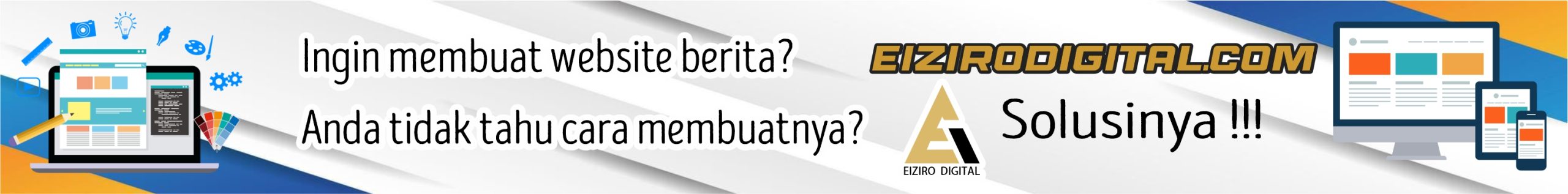Oleh: Ummu Fahhala, S. Pd.
(Praktisi Pendidikan dan Pegiat Literasi)
“Bu, katanya Jawa Barat jadi provinsi paling banyak investasinya di Indonesia, ya?”
Pertanyaan itu meluncur pelan dari seorang siswi kelas X saat jam istirahat. Matanya berbinar, penuh rasa ingin tahu.
Saya tersenyum, menatap wajah muda yang dipenuhi semangat. “Iya, Nak. Nilainya besar sekali, Rp77,1 triliun. Itu data resmi dari Menteri Investasi, Bapak Rosan Roeslani, Jumat 17 Oktober 2025.”
Gadis itu manggut-manggut, lalu bertanya lagi, “Berarti rakyatnya makin sejahtera dong, Bu?”
Pertanyaan itu menampar sunyi ruang kelas. Saya diam sejenak, menatap papan tulis yang masih bertuliskan rumus-rumus fisika. Di dada saya, ada sesuatu yang bergolak, antara bangga dan ragu.
Kilau Angka dan Bayangan di Baliknya
Jawa Barat kembali menjadi sorotan. Angka investasi sebesar Rp77,1 triliun menjadikannya provinsi dengan realisasi investasi tertinggi di Indonesia.
Tokoh Jawa Barat menyebut capaian ini sebagai bukti bahwa iklim investasi di Jabar ramah dan aman.
Namun, di balik kilau angka itu, ada tanya yang tak bisa disembunyikan: Apakah benar semua itu berbuah kesejahteraan untuk rakyat kecil? Ataukah hanya menjadi pesta bagi segelintir pemilik modal besar yang menancapkan kukunya di bumi Parahyangan?
Pagi itu, saya menyusuri jalan di kawasan industri Rancaekek. Asap pabrik menebal, suara mesin berdengung.
Di sisi jalan, beberapa ibu duduk beralaskan kardus menjajakan gorengan. “Dulu saya kerja di pabrik, Bu,” ujar salah satunya, tersenyum getir.
“Sekarang banyak pekerja baru dari luar, perusahaan katanya mau efisien,” lanjutnya.
Saya mengangguk pelan. Kata “efisien” dalam bahasa ekonomi sering berarti menghemat biaya dengan menekan upah buruh.
Inilah wajah paradoks dari investasi: pembangunan tumbuh, tapi perut rakyat tetap keroncongan.
Jejak Kapitalisme yang Membekas
Dari sinilah mulai dipahami bahwa menjadi juara investasi bukan semata prestasi. Itu juga peringatan bahwa daerah kita sedang giat melayani para pemilik modal, bukan semata rakyatnya sendiri.
Sistem ekonomi kapitalis memang begitu. Ia menjanjikan kemakmuran, tapi sering meninggalkan luka.
Dalam sistem ini, sumber daya alam bisa dikuasai individu atau korporasi besar. Mereka mengelola, mengeruk, lalu membawa hasilnya keluar negeri.
Lihat saja bagaimana pengelolaan migas berubah sejak UU No. 8/1971 digantikan oleh UU No. 22/2001.
Dulu negara memonopoli demi kebutuhan rakyat. Kini, pintu terbuka lebar bagi swasta dan asing atas nama efisiensi.
Bank Dunia bahkan pernah menjadikan liberalisasi migas sebagai syarat pemberian utang. Akibatnya, rakyat harus membayar mahal untuk energi yang mestinya milik bersama.
Begitulah kapitalisme bekerja secara licin, lembut, tapi mencengkeram kuat.
Suara dari Hati dan Jalan Islam
Di tengah hiruk-pikuk pembangunan, saya teringat sabda Rasulullah Saw.:
“Kaum muslim bersekutu dalam tiga hal: air, padang, dan api.”
(HR. Abu Dawud, no. 3477)
Hadis itu sederhana, tapi dalam.
Air, padang, dan api merupakan tiga hal yang mewakili sumber daya kehidupan.
Rasulullah Saw. menegaskan, ketiganya bukan milik individu, tetapi milik umat.
Dalam sistem Islam, minyak dan gas termasuk kepemilikan umum (milkiyyah ‘ammah).
Negara wajib mengelolanya untuk kesejahteraan rakyat. Keuntungannya harus kembali ke kas negara (baitulmal) untuk membiayai pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan publik.
Swasta boleh membantu, tapi sebatas pekerja kontrak (ijarah), bukan pemilik modal utama.
Sejarah mencatat, Umar bin Khaththab tegas menolak individu yang ingin menguasai sumber air di padang pasir. Ia berkata, “Kalau air itu menghidupi banyak orang, maka tidak boleh seorang pun memilikinya.”
Inilah prinsip keadilan sosial dalam Islam bersifat kuat, tegas, dan berpihak kepada umat.
Sore itu, saya kembali ke rumah dengan kepala penuh renungan.
Angka Rp77,1 triliun masih terngiang, namun wajah-wajah rakyat kecil lebih melekat di ingatan.
Apakah kita benar sedang membangun kemandirian?
Ataukah sedang memperindah panggung bagi para investor?
Investasi dibutuhkan, tapi arah dan kendalinya harus jelas, berpihak pada manusia, bukan pada modal.
Dan hanya sistem yang berpijak pada nilai ilahi yang mampu menjamin itu.
Penutup
Jawa Barat memang ramah dan aman.
Namun, jangan sampai keramahan itu berubah menjadi penyerahan total terhadap kepentingan modal besar.
Kita harus belajar memaknai pembangunan dengan cara yang lebih manusiawi, lebih adil, dan lebih bermartabat.
Islam telah menuntun jalan itu sejak berabad lalu dengan
membangun peradaban dengan keadilan, bukan dengan eksploitasi, yakni
menyejahterakan umat, bukan memperkaya segelintir elit.
Suatu hari, semoga siswi saya itu bisa membaca berita lain yang lebih membahagiakan,
bukan tentang siapa yang paling banyak menanam modal,
tetapi tentang siapa yang paling banyak menikmati hasilnya.